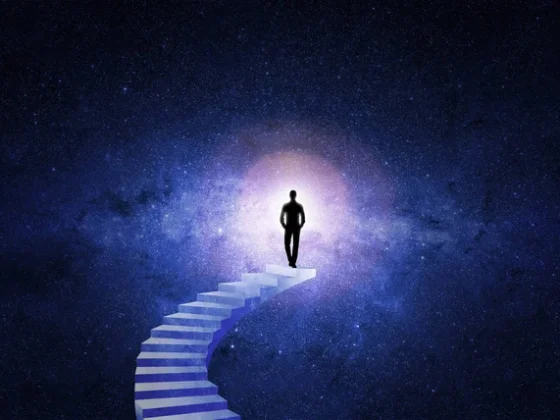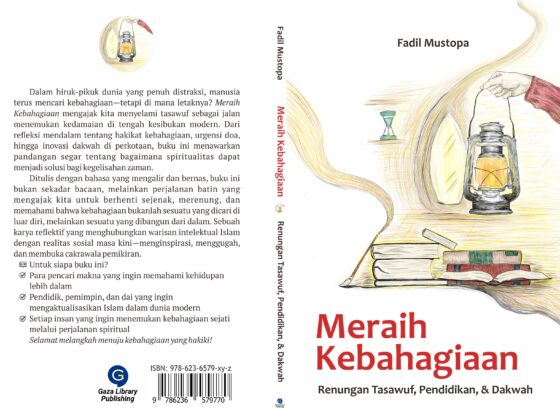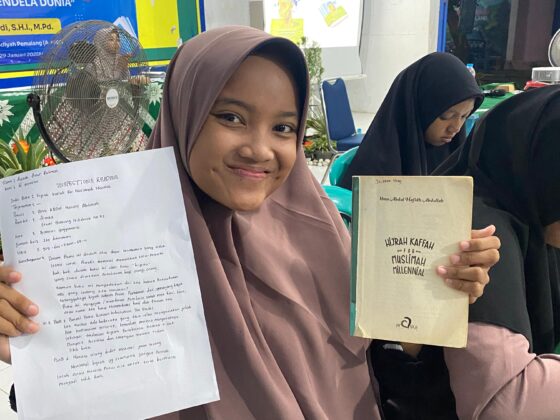Analisis Pemikiran Prof. Musa Asy’ari dalam Buku Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir
Oleh: Alvin Qodri Lazuardy, M.Pd/ Penulis Buku Merawat Nalar Salim
Awalan. Perbincangan mengenai filsafat sering kali memunculkan ketegangan, khususnya dalam konteks Islam. Di satu sisi, terdapat pandangan yang secara tegas menolak filsafat, melihatnya sebagai produk dari peradaban Yunani yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Di sisi lain, ada yang melihat filsafat sebagai jalan untuk memahami lebih dalam aspek kehidupan dan keimanan, mengaitkannya dengan proses berpikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Sebuah pandangan yang dianut oleh Prof. Dr. Musa Asy’arie dalam karyanya Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir, menyatakan bahwa filsafat Islam merupakan manifestasi dari tradisi berpikir Nabi Muhammad saw. sendiri.
Dalam konteks ini, filsafat bukanlah sesuatu yang asing atau terpisah dari Islam, melainkan bagian integral dari ajarannya. Prof. Asy’arie menegaskan bahwa filsafat Islam adalah metode berpikir yang berpijak pada teladan Nabi, suatu sunnah yang mencerminkan proses berpikir kritis, reflektif, dan mendalam. Beliau menggambarkan Nabi Muhammad sebagai sosok yang tidak hanya memimpin umatnya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam kerangka pemikiran yang luhur, yang berakar pada moralitas dan spiritualitas.
Namun, yang menjadi masalah adalah bahwa tradisi berpikir yang diajarkan Nabi ini tidak berkembang di kalangan umatnya. Menurut Prof. Asy’arie, banyak umat Islam yang lebih fokus pada “produk” pemikiran—yakni hasil-hasil praktis tanpa memahami proses intelektual di baliknya. Ini membuat kebudayaan stagnan, menjadikan umat lebih sebagai konsumen daripada produsen peradaban. Dalam pengamatan kritis ini, Prof. Asy’arie mengajak kita untuk kembali menggali metode berpikir Nabi, bukan sekadar meniru hasilnya.
Salah satu landasan penting yang diangkat oleh Prof. Asy’arie dalam membangun filsafat Islam adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad: “Iqra’ bismirabbika aldzii khalaq” (Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan). Ayat ini bukan hanya perintah untuk membaca dalam arti literal, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang pentingnya berpikir kritis dan rasional. Ini menjadi dasar dari apa yang oleh Prof. Asy’arie disebut sebagai metode *rasional transendental*.
Dalam metode rasional transendental ini, ada dua dimensi utama yang diintegrasikan: rasionalitas dan transendensi. Rasionalitas dicapai melalui ijtihad—usaha keras dalam berpikir secara mendalam dan radikal. Sementara transendensi dicapai melalui dzikir—kesadaran akan dimensi gaib dan hubungan dengan Tuhan. Kedua dimensi ini, menurut Prof. Asy’arie, merupakan sunnah berpikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ia menggabungkan pemikiran yang radikal dengan kesadaran spiritual yang mendalam, menciptakan jalan filsafat yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur’an.
Integrasi antara rasionalitas dan transendensi inilah yang menjadi inti dari filsafat Islam. Sebuah filsafat yang tidak hanya menganalisis dunia materi dan fenomena, tetapi juga menghubungkan analisis itu dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Filsafat Islam, dalam pandangan Prof. Asy’arie, adalah sebuah sistem pemikiran yang terstruktur, yang mencakup tidak hanya logika dan argumen, tetapi juga hikmah profetik dan nilai-nilai spiritual.
Namun, meskipun filsafat Islam telah memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Nabi, tidak dapat dipungkiri bahwa di sepanjang sejarah, ada resistensi terhadap penggunaan istilah “filsafat” dalam Islam. Istilah ini sering kali dianggap sebagai produk asing yang tidak sejalan dengan tradisi Islam. Namun, Prof. Asy’arie menegaskan bahwa substansi dari filsafat Islam tidak akan pernah hilang, terlepas dari berbagai gugatan atas istilah yang digunakan. Esensi dari pemikiran Nabi tetap abadi dan terus relevan dalam kehidupan umat Islam.
Dari perspektif ini, kita bisa melihat bahwa filsafat Islam, dalam maknanya yang sejati, tidaklah berakar pada tradisi filsafat Yunani, melainkan merupakan perwujudan dari ajaran Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad. Ini adalah filsafat yang lahir dari akal yang salim—akal yang murni dan jernih, serta diarahkan oleh nilai-nilai ilahiah. Nabi Muhammad, melalui contoh hidupnya, menunjukkan bagaimana proses berpikir yang benar dapat mengarahkan manusia pada kebijaksanaan dan kebenaran.
Namun, tantangan bagi umat Islam saat ini adalah bagaimana menghidupkan kembali tradisi berpikir ini. Bagaimana kita bisa kembali kepada proses berpikir yang mendalam dan tidak sekadar mengulang-ulang produk pemikiran yang sudah ada? Sebagaimana dikatakan Prof. Asy’arie, tanpa menguasai proses berpikir yang benar, umat Islam akan terus menjadi konsumen peradaban, bukan produsen. Kebudayaan kita akan stagnan, dan kreativitas intelektual akan mampet.
Untuk itu, diperlukan upaya serius dalam merevitalisasi tradisi berpikir ini. Kita perlu mengajarkan kepada generasi muda bahwa berpikir kritis dan mendalam adalah bagian dari sunnah Nabi, sama pentingnya dengan aspek ibadah lainnya. Filsafat Islam bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dijauhi, tetapi justru merupakan alat untuk memahami dunia dan kehidupan dengan lebih baik, dalam cahaya ajaran Al-Qur’an dan sunnah.
Akhiran, filsafat Islam mengajak kita untuk berpikir secara rasional, namun tetap terhubung dengan transendensi. Ini adalah warisan intelektual yang luhur, yang berakar pada ajaran Nabi Muhammad dan seharusnya menjadi landasan bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam ke depan. Dengan menghidupkan kembali tradisi berpikir ini, umat Islam dapat kembali menjadi produsen peradaban dalam cara berpikir serta cara pandangnya.
Referensi:
Musa Asy’arie, Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir, (Sleman: LESFI, cetakan ke-vi, 2017)